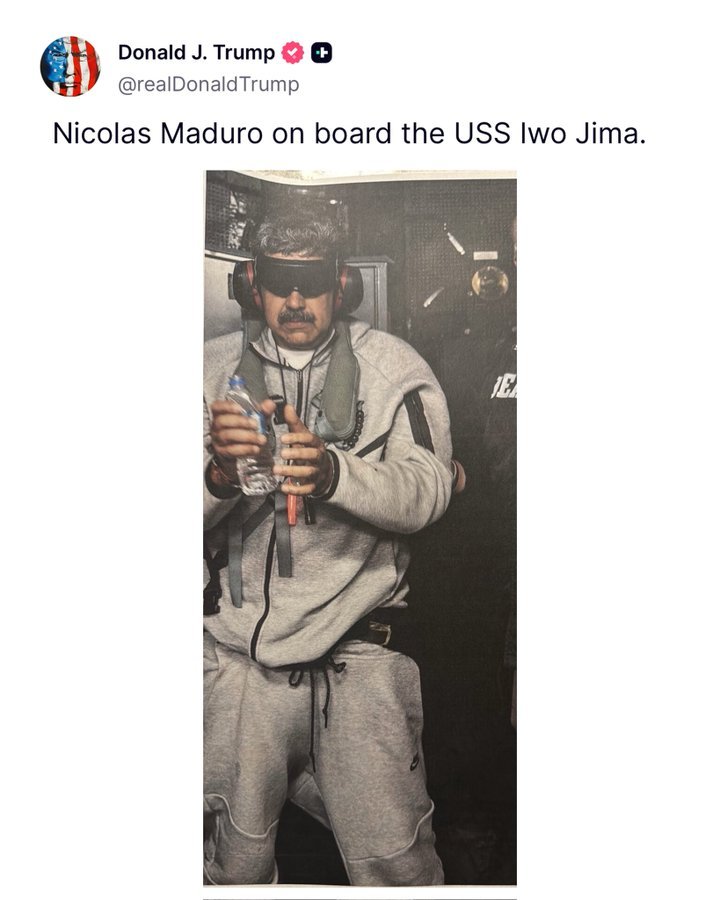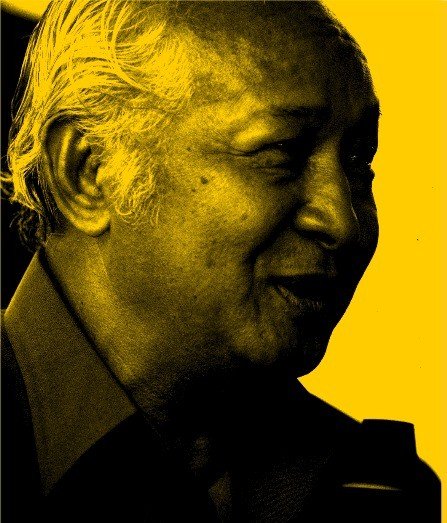Narasi tentang kegagalan reformasi, kebangkitan kembali Orde Baru, dan memburuknya demokrasi Indonesia kembali bergema di berbagai ruang diskusi dan aksi gerakan rakyat sepanjang bulan Mei ini. Narasi ini tentu tidak muncul tanpa sebab. Ia lahir dari evaluasi atas capaian reformasi 1998 yang direfleksikan dalam konteks kondisi sosial-politik hari ini.
Sebagai pengingat, berikut adalah tujuh tuntutan utama gerakan reformasi 1998:
- Penghapusan dwifungsi ABRI (militer kembali ke barak);
- Pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya;
- Amandemen UUD 1945;
- Desentralisasi dan otonomi daerah;
- Penegakan supremasi hukum dan HAM;
- Pemilu yang demokratis dan multipartai; dan,
- Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dua puluh tujuh tahun berlalu, namun jika kita refleksikan, capaian reformasi jauh dari tuntas—bahkan cenderung mundur. Militer kembali merambah ruang-ruang sipil dan posisi strategis di pemerintahan, diperkuat oleh revisi UU TNI 2024 yang memberi ruang legal lebih besar bagi perwira aktif untuk menduduki jabatan sipil. Soeharto tidak pernah diadili, bahkan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Upaya mengembalikan UUD 1945 ke versi awal pra-reformasi kembali menguat lewat wacana amandemen terbatas.
Pasca disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja, semangat desentralisasi terkikis. Pemerintah pusat menarik kembali banyak kewenangan daerah, menjadikan sentralisasi kekuasaan semakin menguat. Praktik pelanggaran etika hukum ditunjukkan secara vulgar oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara batas usia capres, dan pelanggaran HAM berat masa lalu—seperti tragedi 1965, Talangsari, dan penculikan aktivis—tidak menunjukkan perkembangan berarti dalam penegakannya. Sistem elektoral yang seharusnya menjamin demokrasi justru berubah menjadi ajang transaksi kekuasaan, dan KKN yang dulu dipusatkan di lingkaran Soeharto kini terdistribusi merata ke berbagai level kekuasaan.
Yang lebih menyakitkan, banyak tokoh reformasi yang dulu lantang melawan Orde Baru, kini justru satu barisan dengan penculiknya.
Dari Depolitisasi ke Ketiadaan Subjek Politik
Mengatakan reformasi gagal bukanlah ekspresi pesimistis semata, melainkan pembacaan kritis atas kegagalan struktural dan kultural dalam membangun demokrasi substantif. Namun kegagalan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan produk dari kondisi material dan historis yang lebih dalam.
Hampir dari kita semua–yang baca tulisan ini–tau, salah satu dosa besar Orde Baru adalah penghancuran politik rakyat. Melalui pembantaian massal 1965-1966 dan politik depolitisasi selama lebih dari tiga dekade, Orde Baru sukses menciptakan masyarakat apolitis. Politik dimonopoli oleh negara dan militer, sementara rakyat dijauhkan dari kehidupan politik sebagai subjek. Hasilnya adalah generasi yang tercerabut dari kesadaran politik, memandang politik hanya sebagai urusan elit dan bukan ruang perjuangan untuk menentukan arah hidup bersama.
Sayangnya, Reformasi 1998 gagal membongkar warisan depolitisasi ini. Rezim berganti, namun struktur kekuasaan dan budaya politik yang diwariskan Orde Baru tetap bercokol. Memang terjadi transisi menuju demokrasi tapi, oligarki tetap menjadi logika dasar yang menggerakkan politik Indonesia pasca-otoritarianisme (Robison & Hadiz 2004: 3). Bahkan dalam tubuh gerakan itu sendiri, sikap depolitisasi seringkali hadir secara terselubung. Meski ada geliat aksi massa, pengadvokasian kasus, dan pengorganisiran, mayoritas gerakan menghindari politik formal—terutama partai—dengan dalih idealisme atau kekecewaan terhadap partai-partai korup.
Kecenderungan ini menyebabkan energi sosial-politik yang tumbuh dari bawah tidak pernah mengalami transformasi ke arah yang lebih maju dan strategis. Politik formal dibiarkan jadi urusan oligarki dan borjuasi. Sementara di akar rumput, kantong-kantong kolektif dan organisasi massa terus menggelar pendidikan politik, menyusun siasat ekonomi perlawanan, dan menyebar agitasi. Tapi semua itu masih berhenti di level kesadaran sektoral/ekonomistik, tidak menjelma menjadi konsolidasi politik kelas yang meluas. Seperti dicatat Timo Duile dan Jonas Bens (2017), demokrasi Indonesia dibangun di atas “conflictual consensus” yang menyembunyikan kontradiksi kelas dan memperlihatkan “praktik demokrasi di Indonesia masih diwarnai oleh tingkat depolitisasi yang tinggi, yang menghambat partisipasi politik rakyat secara substansial.”
Gejalanya tampak telanjang saat pemilu tiba. Tak jarang warga dampingan, yang selama ini hidup bersama kolektif progresif, yang menerima materi perjuangan kelas, sejarah gerakan rakyat, atau ekonomi-politik, justru memilih menjadi tim sukses Prabowo—atau calon-calon borjuis lain yang jelas-jelas bertentangan dengan agenda emansipatoris. Ada pula yang, karena frustasi berbelok ke organisasi fundamentalis, atau justru bergabung ke ormas-ormas prokem yang meresahkan.
Hal ini menunjukkan satu hal penting: bahwa kesadaran politik yang terbangun bukanlah hasil dari pendidikan satu arah. Ia bukan sekadar menyampaikan pengetahuan kepada yang belum tahu. Politisasi adalah proses dialektis, yang hanya bisa hidup jika disertai pengalaman bersama dalam perebutan posisi kekuasaan di segala medan.
Gerakan Tanpa Orientasi Politik; Oligarki Mengisi Kekosongan
Salah satu kelemahan utama gerakan pasca-reformasi adalah ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk membangun kekuatan politik formal yang terorganisir. Partai politik dianggap korup dan tidak relevan lagi. Namun, tanpa kehadiran kekuatan alternatif di arena politik formal, ruang kekuasaan justru kembali diisi oleh elite lama dan kroni Orde Baru.
Tidak seperti gerakan rakyat, para oligark justru serius membangun infrastruktur politiknya: masuk dan mendanai partai politik pasca-reformasi, bahkan menciptakan partai baru untuk mengamankan kepentingan kelas mereka. Partai menjadi kendaraan formal bagi akumulasi kekuasaan dan modal mereka. Bukan hanya partai besar, hampir seluruh spektrum politik formal hari ini tunduk pada kepentingan oligarki. Oligarki merujuk pada sistem kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok kecil elit, yang menggunakan kekayaan dan posisi strategis mereka untuk mendominasi proses politik dan mempertahankan kepentingan mereka di atas kepentingan publik (Robison & Hadiz 2004: 3). Makanya menjadi hal wajar, kalau tidak ada partai yang mewakili kepentingan rakyat pekerja saat ini.
Situasi ini yang membuat percakapan tentang value, ideologi, spektrum politik kiri-kanan-tengah, menjadi seolah tidak relevan. Politik direduksi menjadi kompetisi pragmatis antar elit. Bahkan Romo Franz Magnis Suseno—yang dikenal sebagai tokoh anti-komunis—pun pernah menyatakan bahwa “Indonesia kini butuh partai kiri.” Bahkan ia pun bisa berpadangan kalau kekuatan oligarki yang sudah terkonsolidasi begitu solid hanya bisa dihadapi dengan partai politik progresif—yang hingga kini belum benar-benar ada.
Menghindari partai politik justru membuat gerakan kehilangan alat penting untuk meradikalisasi perjuangan. Seperti dikatakan Rosa Luxemburg, yang kurang lebih [tanpa partai, gerakan massa kehilangan arah]. Bisa kita refleksikan perjuangan massif gerakan rakyat selama beberapa tahun terakhir: RefromasiDikorupsi, MosiTidakPercaya, DaruratDemokerasi, IndonesiaGelap, dan penolakan-penolakan terhadap revisi UU TNI. Apa yang benar-benar kita pelajari? Kenapa organisasi-organisasi rakyat justru melemah alih-alih semakin menguat dan anggotanya bertambah signifikan?
Gramsci juga menekankan terkait partai, “partai politik adalah bentuk modern dari intelektual kolektif: ia merupakan sarana untuk merumuskan dan menyebarluaskan ide serta kehendak dari suatu kelompok, kelas, atau lapisan sosial tertentu” (Gramsci, Prison Notebooks, Q12 §1, Hoare & Nowell Smith 1971: 15). Dia melihat partai sebagai alat yang mengorganisasi ide, membangun hegemoni, dan merebut kekuasaan. Tanpa adanya partai, akibatnya, perjuangan politik yang dilakukan di jalanan, tanpa strategi perebutan kekuasaan, menjadi terputus dari struktur penentu kebijakan. Gerakan rakyat menjadi menjadi semacam ritual simbolik yang terulang tiap ada kebijakan tidak pro-rakyat muncul, namun tidak mampu membangun kekuatan yang mengakar dan berpengaruh apalagi ancaman terhadap kekuasaan.
Partai Bukan Gagasan Baru Hanya Diabaikan Saja
Gagasan tentang partai bukan hal baru. Sejak era perjuangan kemerdekaan hingga Orde Lama, partai adalah alat utama perjuangan rakyat. Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan dalam wawancaranya dengan Max Lane, “Orang kiri yang tidak berpartai tidak akan pernah bisa mengubah apapun.” Di bawah kapitalisme neoliberal yang represif, gerakan rakyat tanpa partai–paling tidak 10 tahun terakhir kita saksikan–justru makin tercerai-berai, reaksioner, ter-subordinasi donor, dan terjebak dalam siklus perlawanan yang tanpa henti macam Sisifus.
Seperti disinggung di atas, kalau perjuangan ekonomi tidak serta merta membentuk kesadaran kelas. Lenin mengingatkan bahwa, “Kesadaran Sosial-Demokratik [revolusioner] tidak mungkin muncul secara spontan dari kalangan buruh sendiri. Ia harus dibawa dari luar.” (Lenin 1902: 17). Artinya, kesadaran kelas proletariat tidak tumbuh secara otomatis dari eksploitasi, tetapi harus dibentuk secara aktif dan terorganisir—melalui partai.
Sudah banyak format alternatif dicoba di luar partai—kolektif, komunitas, kooperasi, bahkan proyek eskapisme yang menolak sistem sambil menciptakan dunia alternatif yang demokratis. Namun selama negara kapitalis dan sistem politik yang dikuasai oleh para oligarkh masih ada, mereka akan terus kembali—mengetuk pintu belakang kolektif/organisasi kita dengan wajah yang lebih ramah dengan rupa paling realistis dan masuk akal untuk menerima mereka dengan suka cita.
Saatnya Memanifestasikan Partai
Kita tidak sedang mengingkari kerja-kerja penting yang telah dilakukan oleh gerakan rakyat selama hampir tiga dekade terakhir—dari aksi massa, pendampingan hukum, pendidikan politik, hingga konsolidasi lintas daerah. Semua itu membentuk basis resistensi yang penting. Namun kerja-kerja tersebut tetap terbatas dalam kerangka reaktif—merespons kebijakan, menyikapi represi, mengisi kekosongan layanan publik—tanpa strategi merebut ulang kekuasaan negara yang kini dikendalikan sepenuhnya oleh para oligark.
Membangun partai politik bukan solusi instan, apalagi satu-satunya. Tapi dalam struktur negara kapitalis yang masih membuka ruang legal-formal, partai adalah prasyarat objektif untuk merumuskan dan merepresentasikan kepentingan politik kelas (pekerja) secara kolektif dan terorganisir. Dan justru bentuk inilah yang diabaikan atau bahkan ditolak oleh mayoritas gerakan pasca reformasi, sementara kelas penguasa mengerjakannya dengan sistematis dan konsisten.
Tanpa ekspresi politik formal yang mampu bertarung dalam arena negara, perjuangan akan terus berulang dalam bentuk perlawanan temporer—terorganisir di tingkat lokal, tapi tidak punya orientasi strategis jangka panjang. Dalam kondisi seperti itu, memperingati reformasi hanya akan menjadi ritual tahunan, sementara arsitektur kekuasaan makin dikunci oleh oligarki yang tidak pernah meninggalkan arena negara.
Waktunya tidak banyak. Diskursus tentang partai harus mulai dibuka dan diluaskan kembali—bukan dalam kerangka romantik, bukan dalam bentuk kultus atas bentuk-bentuk lama, tapi sebagai kebutuhan strategis yang muncul dari ketidakhadiran subjek politik alternatif dalam konstelasi kekuasaan. Perlu menjadi catatan penting, pembentukan partai tidak bisa dilihat sebagai proyek elektoral semata, melainkan sebagai upaya membangun kekuatan politik rakyat yang sanggup mempertahankan diri, bahkan dalam kondisi represi terbuka. Apalagi kalau rezim hari ini memang menunjukkan watak fasis, seperti yang banyak diyakini dan disuarakan oleh para aktivis.
Dalam kondisi seperti itu, partai tak cukup hanya menjadi alat legal; ia harus mengambil bentuk yang sesuai dengan situasi—termasuk kemungkinan untuk mengorganisir pertahanan rakyat (angkat senjata) dalam makna yang sepenuhnya material. Tapi bagaimanapun, intinya saat ini partai itu harus disegerakan.
Daftar Pustaka
Duile, T., & Bens, J. (2017). Depoliticisation and the Political: Civil Society and the Limits of Democratic Transformation in Post-Suharto Indonesia. Asian Studies Review, 41(4), 571–588. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1377191
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q12 §1) (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). London: Lawrence and Wishart.
Lenin, V. I. (1902). What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement. Retrieved from [Marxists Internet Archive]: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/
Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: RoutledgeCurzon.