Peringatan hari kelahiran sastrawan Pramoedya Ananta Toer ke-100 disambut dengan gegap gempita. Memasuki Februari, wajah Pram ramai menghiasi timeline media sosial. Buku-bukunya yang sempat dilarang Orde Baru dicetak ulang. Diskusi-diskusi dilakukan secara simultan di berbagai kota, salah satunya yang dihelat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan berkat kerja sama sembilan organisasi gerakan rakyat yang terdiri dari serikat buruh, organisasi mahasiswa, dan konfederasi gerakan rakyat.
Acara bertajuk “Satu Abad Kelahiran Pramoedya Ananta Toer” itu diisi oleh kuliah umum Max Lane, seorang indonesianis, kawan baik Pram sekaligus penerjemah tetralogi Pulau Buru ke bahasa Inggris. Beliau juga menulis buku Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia, yang menganalisis karya-karya Pram tentang gagasan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Muslim Silaen dari BPN KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) berkesempatan mewawancarai Max Lane beberapa hari sebelum acara itu dimulai. Bertempat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dengan ditemani soda dingin, kami mulai obrolan ini. Berikut wawancara lengkapnya:
Muslim Silaen (MS): Awal mengenal sosok Pramoedya bagaimana dan kapan? Bisa diceritakan. Kita mulai dari situ dulu ya.
Max Lane (ML): Dulu, sebagai mahasiswa di Australia, kita semua harus baca sastra Indonesia. Jadi kalau kenal orangnya lewat buku-bukunya, sudah sejak di universitas waktu saya masih muda. Tapi kalau ketemu orangnya sendiri, saya pertama kali ketemu pada tahun 1980 (setelah Pram keluar dari Pulau Buru). Waktu itu saya staf di Kedubes Australia di Indonesia.
Di tahun 1980 itu saya ada kenalan, namanya Raharjo Suwandi. Saya kenal dengan dia pas di Canberra ketika dia sedang menjadi mahasiswa S3 di ANU (Australian National University). Suatu hari dia mengajak saya untuk ketemu Pram, “Max, kamu mau ketemu Pramoedya Ananta Toer gak?” Saya jawab, “Jelas saya mau.” Raharjo bisa punya akses bertemu dengan Pram, karena sebelum tahun 1965, dia adalah mahasiswanya Pram di Universitas Res Publica (sekarang Universitas Trisakti). Pramoedya adalah salah satu dosen di universitas itu.
Muslim Silaen (MS): Dalam proses di universitas, Pram menjadi salah satu penulis yang Bung gemari?
Max Lane (ML): Wajib. Kita semua wajib baca Pram. Karena saya mahasiswa di jurusan Studi Indonesia. Saya jadi mahasiswa tahun 1969–1972. Pada waktu itu, meskipun di Australia semua orang tahu banyak orang yang ditahan di Pulau Buru, itu belum jadi isu. Jadi dosen-dosen saya, tidak ada yang terlalu peduli tentang orang ditangkap waktu itu.
Muslim Silaen (MS): Apa karya pertamanya Pram yang Bung baca?
Max Lane (ML): Waduh, kamu ingin saya ingat buku apa yang saya baca di tahun 1969. Saya kira yang kita baca waktu itu yang wajib, kalau tidak salah Cerita dari Blora, Keluarga Gerilya.
Muslim Silaen (MS): Bung juga kan penerjemah karya-karya pertama Pram ke bahasa Inggris?
Max Lane (ML): Itu di tahun 1981. Waktu itu di Hutan Kayu saya ketemu Pramoedya, Jusuf Ishak, dan Hasyim Rahman. Mereka kasih lihat saya naskah Bumi Manusia. Saya baca naskah itu, saya pikir buku ini sangat penting dibaca oleh orang yang ada di luar Indonesia. Sebelumnya saya juga sudah menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Karyanya Rendra, Kisah Perjuangan Suku Naga, suatu satire Rendra terhadap pemerintahan Soeharto yang ia tulis tahun 1973–1974.
Karena buat saya, ini suara Indonesia yang sesungguhnya. Di tahun 1980-an yang dikenal di dunia Barat, terutama di tempat saya tinggal di Australia, adalah Soeharto. Dia dikenal sebagai diktator, orang yang memimpin pembunuhan massal tahun 1965–1966, orang yang melakukan referendum palsu di Papua, orang yang mengirim tentara ke Timor Leste. Jadi citra Indonesia di luar justru sangat negatif.
Di luar Indonesia, tidak ada yang memandang Indonesia secara positif. Saya sendiri, karena sudah bolak-balik ke Indonesia sejak tahun 1969, ketemu mahasiswa, Rendra, orang-orang yang kritis, maka saya tahu kalau Soeharto tidak mewakili masyarakat Indonesia. Waktu saya baca naskah Bumi Manusia, buat saya ini adalah Indonesia yang harus dikenal dunia luar. Kalau dunia luar hanya kenal Soeharto, maka itu tidak akan bisa kenal Indonesia. Kalau kamu mau cek reaksi orang Barat terhadap karya Pramoedya, bagus kamu cek di Amazon.com. Kamu cari This Earth of Mankind, lalu kamu lihat komentar-komentarnya.
Muslim Silaen (MS): Di salah satu buku Bung, Indonesia Tidak Hadir di Bumi Manusia, Pram mempunyai posisi yang spesial dalam perkembangan sejarah Indonesia. Bisa dielaborasi, Bung?
Max Lane (ML): Karya-karya Pramoedya, apalagi yang dia tulis di Pulau Buru, ada tujuh naskah yang ditulis di Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Arok Dedes, Arus Balik, dan Mangir. Dari Arok Dedes, Arus Balik, Mangir, dan Tetralogi itu, latarnya abad ke-13 sampai abad ke-20. Sebenarnya ada satu lagi, Mata Pusara, tapi naskahnya hilang di Pulau Buru.
Dari karya-karya itu kita bisa mengerti garis besar sejarah Nusantara, karena belum ada Indonesia. Yang paling mendetail tentu adalah Tetralogi Buru, bercerita tentang Nusantara di awal abad ke-20. Yang buat saya geleng-geleng kepala, Pram bisa menggambarkan dengan jelas asal-usul Anda (sebagai nation).
Sebelum tahun 1920, katakanlah, tidak ada orang Indonesia di atas bumi ini. Tidak ada satu orang pun Indonesia; orang Jawa ada, orang Bali ada, orang Aceh ada, tapi tidak ada sama sekali orang Indonesia. Dari zaman Kartini, Tirto Adhi Suryo, atau semua figur yang ada di novel Pram (Tetralogi Buru), tidak ada satu orang pun dari mereka semua yang tahu bahwa suatu hari akan ada Indonesia. Minke, Nyai Ontosoroh, mereka tidak punya bayangan bahwa akan ada suatu negeri, suatu kebudayaan, yang namanya Indonesia.
Empat karya dalam tetralogi itu luar biasa, tapi bagi saya yang paling jenius dan brilian adalah Bumi Manusia, meskipun Rumah Kaca jauh lebih kompleks. Ketika kita baca Bumi Manusia sambil merenungkannya, kita akan melihat bagaimana seorang pemuda (Minke), tamatan HBS, anak Bupati, berhenti menjadi orang Jawa dan mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Karena ketika di Rumah Kaca, dia (Minke) sudah bukan orang Jawa lagi. “Saya mau jadi manusia merdeka, saya mau jadi manusia modern, saya mau jadi manusia berilmu pengetahuan.”
Kita juga bisa melihat semua unsur masyarakat, khususnya di Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa—semua iklim, pengalaman, kegiatan—yang bisa menciptakan manusia baru, yang di kemudian hari dikenal sebagai orang Indonesia. Pengalaman pribadinya, pengalaman mengalami penindasan di Belanda, bergaul dengan macam-macam orang, itu mulai terbentuk. Itu menggambarkan bagaimana proses seseorang berubah melampaui identitas tradisionalnya, yang kemudian dialami oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang.
Tapi ada faktor lain yang juga penting dan itu baru muncul di Jejak Langkah: pentingnya berorganisasi. Minke yang sudah dewasa, tidak puas hanya dengan menjadi individu yang merdeka. Dia belum bisa membayangkan tentang Indonesia, tapi dia ingin solusi yang lebih konkret atas ketidakadilan yang dirasakannya. Jawabannya dia temukan di organisasi. Buat saya, hanya Pramoedya yang punya pendekatan tentang sejarah berserikat di Indonesia.
Muslim Silaen (MS): Tirto/Minke mungkin di awal adalah priyayi, karena mereka mempunyai privilege terhadap pendidikan. Di Indonesia sendiri, dalam banyak kesempatan banyak yang menyayangkan kalau sastra tidak masuk kurikulum dan silabus pendidikan. Tapi beberapa tahun terakhir ada program Sastra Masuk Kurikulum, dan Bumi Manusia menjadi salah satu bacaan wajib. Apa tanggapan Bung tentang itu?
Max Lane (ML): Tawaran sastra masuk sekolah itu suatu kemajuan, meskipun belum jadi ya. Menurut saya ini hal yang sangat dasar. Tidak hanya penting untuk Indonesia, tapi untuk semua negeri. Meskipun di negeri imperialis, dari Australia sampai Amerika, dan di negeri Global South seperti Indonesia, konteksnya berbeda, tapi tetap ada persamaan. Dalam proses penciptaan makhluk baru, yaitu nation, karena nation sendiri di seluruh dunia adalah fenomena baru.
Sebelum revolusi Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain, yang namanya nation itu adalah komunitas yang bahasanya sama, kebudayaan sama, kehidupan ekonomi yang bersama—itu belum ada. Misal, Prancis: sebelum revolusi, hanya 30% yang bicara bahasa Prancis. Nation di Prancis juga fenomena baru dari abad ke-18. Deklarasi kemerdekaan Amerika juga abad ke-18, dan itu membutuhkan puluhan tahun agar kebudayaannya mulai muncul, bahkan harus ada perang sipil dulu, dsb. Jadi, nation itu di mana-mana baru, dan di Indonesia sangat baru.
Dalam proses membangun suatu nation, satu hal yang menjadi fondasi adalah memori atau pengalaman bangsa. Memori itu tidak serta-merta datang, apalagi bagi yang baru lahir. Memori itu datang dari mana? Terutama di dunia modern, itu datang dari sastra atau cerita. Orang mengenal cerita masa lalu; tentu saja ada buku sejarah, tapi yang lebih berpengaruh di masyarakat adalah ceritanya.
Orang Prancis mengenal tentang Prancis dari sejarahnya, novel-novelnya, sajak-sajaknya. Makanya di zaman revolusi orang-orang membaca; kalau revolusi sudah lewat dan situasi stabil, generasi ke generasi akan didorong mengenal sejarahnya lewat sastra. Makanya di seluruh dunia, di SMP dan SMA, sastra adalah mata pelajaran wajib.
Hanya satu negeri di mana sastra bukan mata pelajaran wajib: Indonesia. Tapi itu ada sejarahnya. Saya harap ke depan ada yang meneliti secara lebih komprehensif, karena saya hanya samar-samar mengerti. Tahun 1950-an dan 1960-an, mata pelajaran sastra ada di sekolah di Indonesia—meniru kurikulum Barat.
Sepertinya tahun 1970-an kurikulum Indonesia berubah, dan sastra tidak lagi diajarkan. Kesan saya itu bersamaan dengan berkembangnya pengaruh Ali Murtopo (asisten pribadi Soeharto) karena menulis buku Strategi Kebudayaan Nasional. Konsep Ali Murtopo yang jadi konsep Orde Baru: Kebudayaan Indonesia adalah semacam federasi budaya-budaya tradisional etnis, dengan simbol utamanya Taman Mini Indonesia Indah.
Padahal kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan baru. Sebelum ada orang Indonesia, tidak mungkin ada orang Indonesia. Kebudayaan Indonesia pertama mulai berkembang dengan sastranya. Orang mulai menulis—sebenarnya sejak masa Belanda, seperti Kartini, lalu orang Tionghoa di Hindia Belanda, orang Indo, mulai menulis dalam bahasa Melayu: roman, sajak, cerpen, surat kabar.
Kebudayaan Indonesia jadi kebudayaan yang dirasakan, dihayati, dari Aceh sampai pesisir Papua dalam bahasa yang sama. Menyebarnya tulisan dalam bahasa Melayu, fiksi maupun nonfiksi, itu adalah awal kebudayaan Indonesia. Perubahan kebudayaan yang digambarkan oleh Pram dalam tetralogi bukan hanya bahasanya, cara berpikirnya, tapi juga cara berorganisasi itu sendiri.
Elemen-elemen awal budaya Indonesia—sastranya, lagunya, cara bermasyarakat—itu secara Indonesia; bukan Jawa, Dayak, Bali, dsb., tapi Indonesia. Berserikat, berorganisasi menjadi elemen sangat mendasar. Membunuh berorganisasi adalah membunuh budaya Indonesia!
Masalahnya, sejak 1966, sastra tidak diajarkan di sekolah lagi. Jadi jutaan, bahkan puluhan juta anak Indonesia dari generasi ke generasi, tidak diperkenalkan pada sejarah bangsanya sendiri lewat sastra. Maka, sastra harus dikembalikan pada tempatnya, dan berorganisasi harus dihidupkan kembali.
Muslim Silaen (MS): Pram dalam banyak kesempatan (di buku atau wawancara) selalu menyinggung tentang kaum muda/angkatan muda. Menurut Anda, kenapa Pram seolah begitu mempercayai anak-anak muda ini, yang kita tahu memang masih berapi-api? Tapi kita juga tahu kalau kaum muda (di setiap zaman) agak kurang bertanggung jawab dalam banyak hal. Atau yang dia maksud kaum muda itu apa sih?
Max Lane (ML): Itu karena perombakan masyarakat yang besar dalam sejarah Indonesia. Dalam hal itu, Indonesia sedikit unik, dan pelopornya selalu yang muda. Dalam konteks perjuangan kelas di zaman kapitalis juga dipelopori orang muda. Perjuangan pembebasan nasional atau perjuangan di Eropa sejak anti-feodal pun pelopornya orang muda. Itu sangat masuk akal, karena orang yang sudah berumur 30–40 tahun, dalam situasi yang tidak revolusioner, cenderung tidak bergejolak. Sejak usia 10 tahun sudah hidup dalam pengaruh ideologi dominan; biarpun dari kelas proletar setertindas apa pun, belum tentu akan radikal.
Jangan berharap proletar otomatis akan radikal. Tidak. Seluruh konsep pengorganisiran revolusioner yang pernah ada, hasilnya selalu mulai dari kesadaran akan realitas bahwa kesadaran yang muncul secara spontan di masyarakat, termasuk kelas tertindas, rata-rata tidak akan pernah revolusioner.
Untuk situasi Indonesia, cukup hebat karena sejak 1965 hingga sekarang kesanggupan rakyat untuk melawan itu luar biasa, dibandingkan Australia atau Filipina. Rakyat Indonesia melawan terus. Malari melawan, tahun 1980-an perlawanan kaum buruh luar biasa—padahal belum ada serikat. Itu dimuat di koran: buruh perkebunan teh di Jawa Barat mogok, pabrik-pabrik, dsb. Makanya salah satu kebiasaan aktivisme di Indonesia adalah mendampingi kasus.
Mendampingi kasus sudah berlangsung 50 tahun. Kesanggupan rakyat melawan di Indonesia itu sudah organik, sudah bagian dari budaya Indonesia yang muncul di awal abad ke-20. Tapi melawan saja tidak cukup. Kesadaran spontan untuk melawan, itu positif sekali, tapi tidak cukup. Yang harus jadi kesadaran adalah: mau mendirikan masyarakat di mana rakyat tidak perlu melawan lagi. Karena kalau melawan terus, rakyat akan demoralisasi. Jadi, kesadaran spontan mau melawan itu tidak cukup.
Muslim Silaen (MS): Dalam acara “Satu Abad Kelahiran Pramoedya” Anda akan menyampaikan kuliah umum dengan judul “Mencintai yang Belum Tuntas dan Menuntaskannya: Pramoedya, Indonesia, dan Kaum Muda.” Yang belum tuntas dalam hal ini apa sebenarnya? Dan siapa subjek yang harus mencintai dan menuntaskannya?
Max Lane (ML): Kehebatan banyak orang kiri yang saya kenal—Pram, Jusuf, Hasyim—dan sangat mengharukan bagi saya, mereka itu sangat cinta Indonesia. Mereka tahu kalau Indonesia ini belum tuntas. Kalau menggunakan bahasa mereka dulu, revolusi belum selesai. Kalau sekarang, Indonesia sudah ada tapi sebenarnya revolusi nasionalnya belum selesai. Tapi perasaan “belum selesai” itu tidak ada. Orang-orang menerima: ya, beginilah.
Muslim Silaen (MS): Melihat kondisi Indonesia saat ini, apakah Anda masih melihat harapan, paling tidak untuk membicarakan “What is Indonesia’s next progressive agenda?” Atau mungkin sudah ada, dan masih mungkinkah itu dilanjutkan?
Max Lane (ML): Agenda progresif di Indonesia sebagai nation, saya hanya bisa membayangkan garis besarnya saja. Itu pun masih kabur bagi saya. Agenda gerakan itu lebih jelas. Sudah berorganisasi secara nasional, serikat rakyat non-pejabat bersatu mengorganisasi diri. Yang saya tidak bisa jawab secara konkret itu, kalau ada partai baru atau gerakan baru (organisasi nasional), tuntutan-tuntutan ekonomi dan politiknya yang pertama apa?
Di bidang budaya lebih jelas: sastra harus masuk sekolah. Segala macam isi pendidikan yang mendorong orang berpikir kritis itu bukan hal yang nanti, tapi harus jadi tuntutan sekarang. Tapi kalau sudah di bidang ekonomi, itu sulit. Saya rasa, gerakan perlu buat kongres besar untuk memperdebatkan itu. Bukan untuk negosiasi kesepakatan, tapi untuk memperdebatkan: apa sebenarnya jalan, atau rakyat harus menuntut apa sekarang? Warisan 25 tahun terakhir ini di bidang ekonomi masih begitu-begitu saja. Masalah masyarakat semakin bertambah. Masyarakat semakin ruwet, makin banyak kebutuhannya.
Muslim Silaen (MS): Balik ke “mencintai yang belum tuntas dan menuntaskannya.” Tadi belum terjawab, siapa yang akan menuntaskannya?
Max Lane (ML): Ya Anda-anda ini. Pasti rakyat yang tidak muda akan bergabung, tapi yang harus memulai ya yang muda.
Muslim Silaen (MS): Untuk orang-orang yang kecewa dengan Indonesia hari ini mulai timbul. Mungkin nggak mayoritas. Apa pesan, Bung, untuk teman-teman kita yang sudah mulai tidak mencintai Indonesia?
Max Lane (ML): Salah satu pesan terselubung dari Pram dalam Tetralogi Buru: Indonesia dulu tidak ada, kok sekarang ada? Yang menciptakan Indonesia itu siapa? Proses sejarah dan rakyat. Kalau dulu rakyat Indonesia dan pemimpin-pemimpin mudanya bisa menciptakan Indonesia dan kemudian merebut kemerdekaan, itu sangat hebat. Kalau membandingkan dengan negara lain seperti Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, atau India—meskipun sebagai nation mereka belum ada, hanya kerajaan-kerajaan, kumpulan suku-suku, apalah—minimal konsep Jepang ada, Prancis ada, dsb., meskipun nation-nya belum.
Nah, kalau konsep Indonesia itu tidak ada sama sekali. Jadi menciptakan Indonesia itu adalah sesuatu yang super hebat, karena memang dari nol. Dan rakyat, dengan dipimpin oleh pemuda, bisa menciptakan itu. Itu terjadi di awal abad ke-20, di mana ⅔ dunia adalah koloni, dan tidak dipertanyakan siapa-siapa. Untuk orang muda seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, atau siapa saja waktu itu, untuk bisa membayangkan merdeka padahal ⅔ dunia masih dijajah, pede-nya mereka untuk perjuangan itu bisa dibilang sangat fenomenal.
Pesan terselubungnya: dulu bisa, kok sekarang tidak bisa? Harus diadakan kembali, re-created again. Itu masih harus dituntaskan. Memulai kembali perjuangan untuk dituntaskan.
Saya setuju dengan Soekarno: “Nation building belum selesai! Character building belum selesai! Revolusi belum selesai!” Tahun 1965 itu semuanya belum selesai. Sebelum selesai, itu diberhentikan Soeharto. Selama 32 tahun apakah proses penuntasan jalan terus atau berhenti? Dan mungkin malah mundur.
Wawancara ini dilakukan pada 4 Januari 2025 di Jakarta.

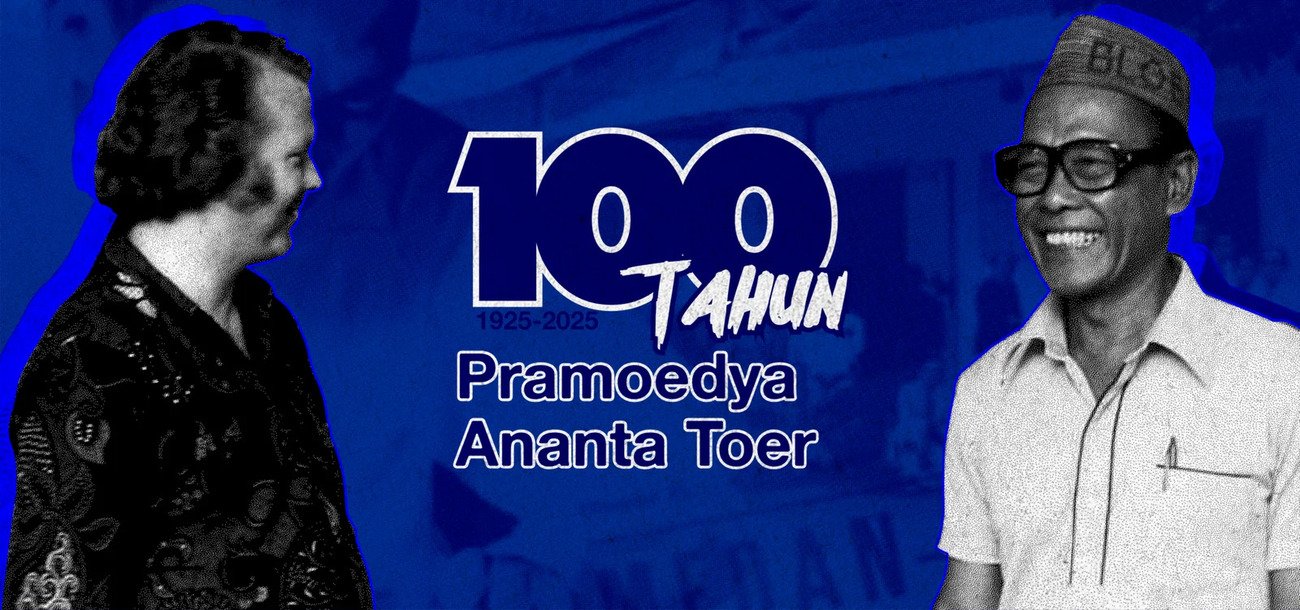

🔥
Kita kaum muda dan sebagai orang terpelajar harus berbuat adil dalam pikiran apa lagi dalam perbuatan,ucap sastrawan pramoedya ananta toer dalam bukunya bumi manusia.
Sebuah teori tanpa praktek hanya menghasilkan sebua onani.
Dalam menjemput yang belum dituntaskan langkah efisien dan alternatif nya yaitu, membangun partai masa rakyat sebagai alat tarung,dalam melawat sistem kapitalisme.