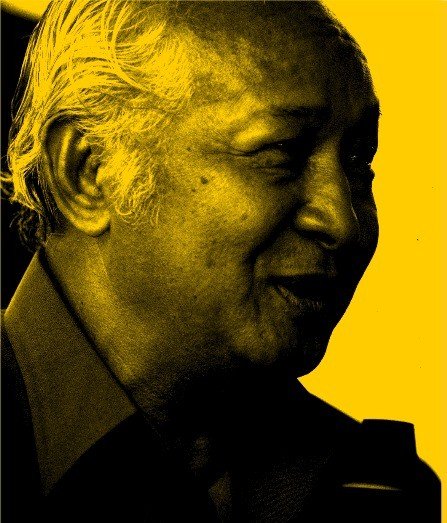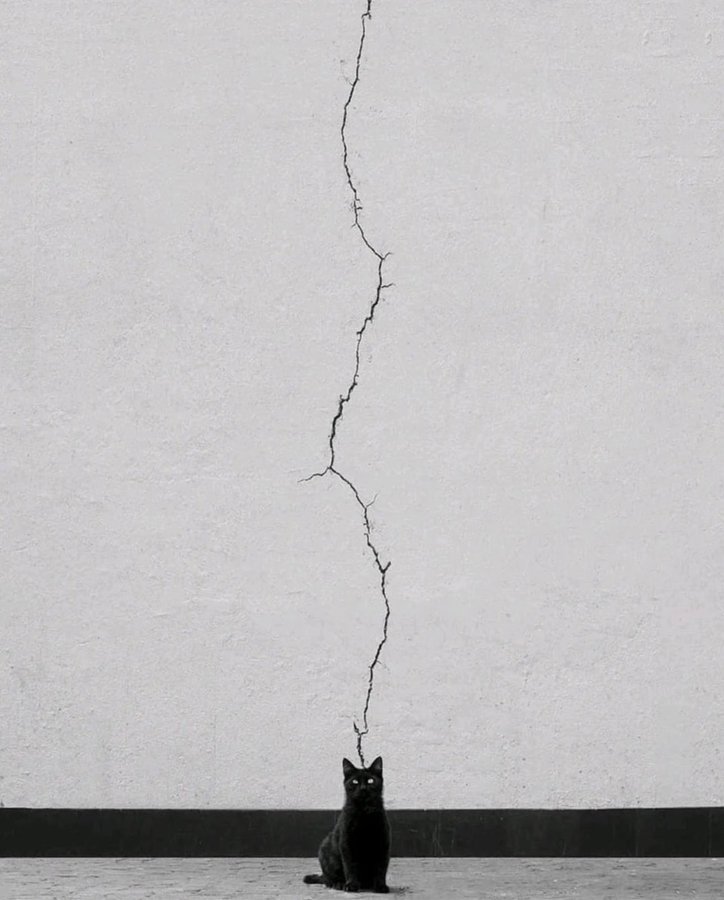“Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. […] Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri.”
Kata-kata di atas adalah sepenggal kalimat yang disampaikan Prabowo dalam memperingati Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2025. Tak ketinggalan retorika-retorika tentang persatuan dan slogan-slogan megalomania yang menyatakan kita bangsa yang besar, dan sebagainya, tapi saya malas kalau harus mengutipkannya juga di sini. Apa yang disampaikannya terasa sumbang, malah menjadikan Pancasila semacam omong kosong. Apalagi ketika dihadapkan dengan tantangan zaman, permasalahan macam apa yang benar-benar dihadapi bangsa ini atau, lebih dispesifikkan, rakyat Indonesia saat ini. Sebagai seorang presiden, ia gagal untuk mengenali apa yang jadi problem dasar rakyat saat ini. Malah tiba-tiba menyasar LSM, antek asing, dan sebagainya. Sesuatu hal yang kontras ketika Pancasila lahir dan disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni.
Karena ini refleksi, maka kita akan menengok kembali kelahiran Pancasila, dan maka dari itu pidato 1 Juni Soekarno menjadi penting. Bagaimana Pancasila lahir untuk menjawab tantangan zaman dan menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia. Pancasila yang waktu itu seperti ini:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Kenapa Soekarno menyusun philosophische grondslag bangsa yang akan lahir itu dengan urutan demikian dan berbeda dengan yang kita ketahui saat ini. Untuk bisa mengetahuinya, maka kita juga perlu tahu dalam kerangka analisis seperti apa yang digunakan oleh Soekarno. Pancasila 1 Juni yang disampaikan oleh Soekarno adalah Pancasila yang dibasiskan pada analisis dialektika-materialisme.
Dialektika adalah alat berpikir kuno sejak zaman Yunani. Jauh sebelum filsafat modern, seorang pemikir bernama Heraclitus (sekitar 535–475 SM) telah menaburkan benih-benih awal dialektika. Ia terkenal dengan ungkapan panta rei, yang berarti “semuanya mengalir”. Bagi Heraclitus, realitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus-menerus bergerak dan berubah. Ia melihat dunia sebagai arena pertarungan dan persatuan antara hal-hal yang berlawanan: panas-dingin, terang-gelap, hidup-mati. Ia percaya bahwa konflik atau pertentangan adalah motor utama perubahan dan esensi dari segala sesuatu. Misalnya, tanpa kegelapan, kita tidak akan mengerti terang. Tanpa sakit, kita tidak akan menghargai sehat. Dalam pertentangan inilah, ia melihat adanya kesatuan yang mendasari. Ide bahwa kontradiksi adalah bagian intrinsik dari realitas, dan justru melalui kontradiksi itulah perubahan dan pemahaman terjadi, merupakan cikal bakal penting bagi gagasan dialektika di kemudian hari.
Transformasi Dialektika Modern: Fichte – Hegel – Marx
Lompatan terbesar dalam evolusi dialektika terjadi pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Jerman, dengan filsuf-filsuf idealis. Awalnya, Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) adalah yang paling eksplisit dalam merumuskan dialektika dengan tiga tahap: tesis, antitesis, dan sintesis. Bagi Fichte, dialektika ini menjelaskan bagaimana kesadaran diri (ego) berkembang. Ego yang awalnya tanpa batas (tesis) akan memunculkan Non-Ego (antitesis) sebagai oposisinya, yang kemudian menghasilkan kesadaran diri yang lebih lengkap melalui batasan atau interaksi di antara keduanya (sintesis). Ini adalah proses yang berulang, di mana setiap sintesis menjadi tesis baru.
Namun, yang benar-benar membawa dialektika ke puncak kompleksitas dan pengaruh adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Meskipun skema “tesis-antitesis-sintesis” sering dikaitkan dengannya, Hegel sendiri tidak menggunakan istilah itu secara harfiah. Ia lebih suka berbicara tentang konsep-konsep seperti:
- Abstraksi – Negasi – Konkretisasi (Abstrakt–Negation–Concrete)
- Ada – Tidak Ada – Menjadi (Sein – Nichts – Werden)
- Dalam dirinya sendiri (an sich) – Untuk dirinya sendiri (für sich) – Dalam dan untuk dirinya sendiri (an und für sich)
Inti dari dialektika Hegel adalah gagasan kontradiksi internal sebagai pendorong perkembangan. Suatu konsep atau ide (yang ia sebut Moment Ketegasan atau yang “dalam-dirinya-sendiri”) selalu mengandung benih kontradiksinya sendiri. Kontradiksi ini akan muncul dan bertentangan dengan dirinya sendiri (yang ia sebut Moment Negasi atau yang “untuk-dirinya-sendiri”).
Puncaknya adalah Moment Sintesis atau Sublasi (Aufhebung). Kata Aufhebung ini sangat penting bagi Hegel karena memiliki makna ganda: menghapuskan/membatalkan, mempertahankan/mengawetkan, dan mengangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, ketika dua ide yang bertentangan berinteraksi, mereka tidak saling menghancurkan begitu saja. Sebagian dari kebenaran masing-masing dipertahankan, dan kebenaran itu kemudian diangkat ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dan lebih komprehensif, menjadi sintesis baru. Sintesis ini bukan sekadar kompromi, melainkan evolusi yang lebih kaya dan konkret dari ide sebelumnya.
Bagi Hegel, seluruh realitas—sejarah, pemikiran, alam, dan bahkan Roh (Geist)—berkembang melalui proses dialektis ini. Sejarah, misalnya, adalah manifestasi dari Roh yang terus-menerus mengatasi kontradiksi dan mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi. Setiap tahap sejarah adalah sintesis dari kontradiksi sebelumnya, dan pada gilirannya, menjadi tesis untuk kontradiksi berikutnya.
Dialektika yang semula bersemayam di alam pemikiran dan abstrak, akan “ditarik” ke bumi, menukik tajam ke dalam kenyataan materiil dan sosial. Inilah yang dilakukan oleh Karl Marx. Ia mengambil kerangka berpikir dinamis dialektika dan “membalikkannya” dari kepala ke kaki. Jika Hegel melihat sejarah dan perkembangan sebagai perjalanan Roh yang sadar diri melalui kontradiksi-kontradiksi ide, Marx berpendapat bahwa bukan ide yang membentuk materi, melainkan kondisi materiil yang membentuk ide. Bukan kesadaran (consciousness) makhluk yang menentukan arah evolusinya, melainkan benturan mereka dengan alam sekelilingnya (relasi dengan materi) yang menentukan arah evolusinya. Bagi Marx, pendorong utama perubahan dan konflik bukanlah pertentangan konsep dalam pikiran, melainkan pertentangan yang nyata dalam struktur ekonomi dan hubungan produksi di masyarakat.
Dengan demikian, dialektika yang tadinya menjelaskan evolusi Geist (Roh/Pikiran), kini akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan sejarah masyarakat kelas, konflik antar kelas, dan revolusi sosial. Itulah yang disebut sebagai dialektika-materialisme.
Refleksi Pancasila 1 Juni
Pancasila, bagi Soekarno, melampaui sekadar common denominator penyatu bangsa; ia adalah serangkaian tahapan dialektika yang memandu evolusi Indonesia menuju kesadaran tertinggi. Dalam merumuskan philosophische grondslag sebagai kerangka dialektika bangsa, Soekarno tidak berpijak pada idealisme, melainkan pada fakta objektif (materi). Fakta objektif fundamental sebagai modal berdirinya bangsa baru ini adalah tanah dan realitas geopolitiknya.
Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ernest Renan yang menyoroti pentingnya suatu “jiwa” (esprit) atau “prinsip spiritual” bangsa yang terbentuk dari warisan sejarah dan keinginan untuk hidup berdampingan di atas wilayah geografis yang sama. Selain itu, gagasan Friedrich Ratzel tentang negara sebagai organisme geografis yang membutuhkan ruang hidup (Lebensraum) turut mempengaruhi visi Soekarno akan pentingnya kesatuan teritorial dan keutuhan wilayah sebagai prasyarat eksistensi dan perkembangan bangsa.
Justru karena didasarkan pada realitas objektif inilah Soekarno menempatkan kebangsaan sebagai butir pertama Pancasila, menegaskan bahwa Indonesia dan seluruh cita-cita luhurnya harus dibangun di atas pondasi tanah air yang kokoh dan bukan di atas khayalan yang rapuh.
Soekarno juga dengan tegas mengingatkan bahwa api nasionalisme yang membara berisiko membakar peradaban di sekitarnya. Oleh karena itu, nasionalisme ditempatkan di tengah-tengah taman sarinya internasionalisme. Ia memahami bahwa nasionalisme yang mengisolasi diri dari humanisme internasional akan membusuk menjadi bangkai fasisme seperti yang terjadi dengan Nazi. Mengutip Mahatma Gandhi, Soekarno kerap menegaskan bahwa “my nationalism is humanism.” Inilah yang kemudian tercermin dalam butir kedua Pancasila: Perikemanusiaan.
Setelah manusia memijakkan kakinya pada tanah kebangsaan dan menjaga dari ancaman chauvinisme dengan taman sari kemanusiaan, barulah manusia Indonesia siap berpikir kreatif dan kolektif untuk membangun kualitas hidupnya. Proses dialektis ini memastikan bahwa fondasi bangsa yang kuat tidak hanya bertumpu pada identitas diri, tetapi juga terintegrasi dalam visi kemanusiaan universal, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan.
Mufakat atau Demokrasi. Setelah landasan kebangsaan dan kemanusiaan kokoh, Soekarno mengarahkan perhatian pada bagaimana bangsa yang baru ini akan mengatur dirinya sendiri. Melalui mufakat atau demokrasi—sebuah refleksi dari pemikiran kreatif dan kolektif—lahirlah inovasi, termasuk perkembangan sains dan teknologi, yang pada tujuannya bukan hanya mensejahterakan kehidupan manusia, tetapi juga menghapuskan eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme). Ini secara tegas menegaskan bahwa negara yang dibangun haruslah berlandaskan demokrasi.
Bagi Soekarno, demokrasi tidak hanya berarti demokrasi politik—di mana kekuasaan tidak dimonopoli segelintir individu atau kelompok identitas—melainkan setiap warga negara memiliki kesamaan hak untuk berpartisipasi dan memimpin. Lebih jauh lagi, ia menekankan pentingnya demokrasi ekonomi, di mana kekayaan dan sumber daya tidak hanya dikuasai oleh kelas tertentu.
Puncak dari dialektika kebangsaan Soekarno adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan terpenuhinya prasyarat-prasyarat sebelumnya—nasionalisme yang inklusif, internasionalisme yang humanis, serta demokrasi politik dan ekonomi—barulah kondisi adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Keadilan sosial ini merupakan fondasi material yang membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan eksploitasi, sehingga mereka dapat mencapai potensi tertinggi sebagai manusia.
Ketika persoalan-persoalan material dan ketidakadilan telah diatasi, rakyat Indonesia akan bebas sepenuhnya menjalankan keyakinan berketuhanan mereka secara beradab, madani, dan rasional. Dengan demikian, agama tidak akan lagi menjadi “candu” bagi masyarakat, melainkan sebuah manifestasi spiritual yang berkembang dalam konteks kebudayaan dan kemajuan peradaban. Inilah yang Soekarno maksud dengan Ketuhanan yang Berkebudayaan: sebuah keyakinan spiritual yang tumbuh subur dalam masyarakat yang berdaulat, adil, makmur, dan berpengetahuan—jauh dari segala bentuk dogmatisme atau pemanfaatan agama untuk menjustifikasi penindasan.
Kondisi dan Tantangan Saat ini
Melihat kondisi Indonesia hari ini tentu menjadi sangat menyedihkan. Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman fundamental bangsa, kini sering kali hanya diteriakkan sebagai simbol, kehilangan makna substansialnya. Lebih jauh, ia bahkan dijadikan justifikasi untuk membenarkan tindakan represif pemerintah terhadap rakyat. Cita-cita luhur yang mendasari konsepsi Pancasila terasa jauh dari kenyataan yang ada.
Dalam konteks ini, pidato pada perayaan Hari Lahir Pancasila, seperti yang disampaikan Prabowo, menunjukkan kesalahpahaman mendalam terhadap esensi Pancasila yang digagas Bung Karno. Alih-alih mendasarkan analisis pada kondisi material objektif yang nyata dihadapi rakyat, ia justru membangun ancaman imajiner dengan teriakan “asing-asing.” Padahal, di depan mata ada situasi objektif yang sangat nyata dan mendesak: kue ekonomi yang terkonsentrasi ke segelintir elit, kesulitan penyediaan lapangan kerja layak, komersialisasi kebutuhan-kebutuhan dasar, perusakan lingkungan yang masif, ketergantungan pada investasi asing, bahkan praktik bisnis dengan entitas zionis, dsb.
Masalah-masalah ini bukanlah sekadar isu permukaan, melainkan kontradiksi inheren dalam struktur sosio-ekonomi Indonesia saat ini. Ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja layak dan komersialisasi kebutuhan dasar menunjukkan kontradiksi antara kebutuhan rakyat dan logika akumulasi kapital. Ketergantungan pada investasi asing dan praktik bisnis dengan entitas yang secara historis problematis mencerminkan kontradiksi antara kedaulatan nasional dan tekanan kekuatan kapital global. Perusakan lingkungan adalah kontradiksi antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
Kontradiksi-kontradiksi material ini memperlebar jurang kesenjangan dan mengikis demokrasi ekonomi yang dicita-citakan Pancasila. Ketika fokus dialihkan pada ancaman imajiner alih-alih menghadapi kontradiksi material ini secara jujur, proses dialektika bangsa terhambat. Bangsa tidak akan bergerak maju menuju sintesis yang lebih tinggi—yakni masyarakat adil dan makmur yang bebas dari eksploitasi—melainkan justru terjebak dalam ilusi yang makin menjauhkan kita dari Pancasila 1 Juni.
Note: Membaca Pancasila 1 Juni dengan kerangka Diamat pertama kali dibaca penulis dari tweet akun @madilogin_. Silahkan rekan-rekan juga baca versi beliau.