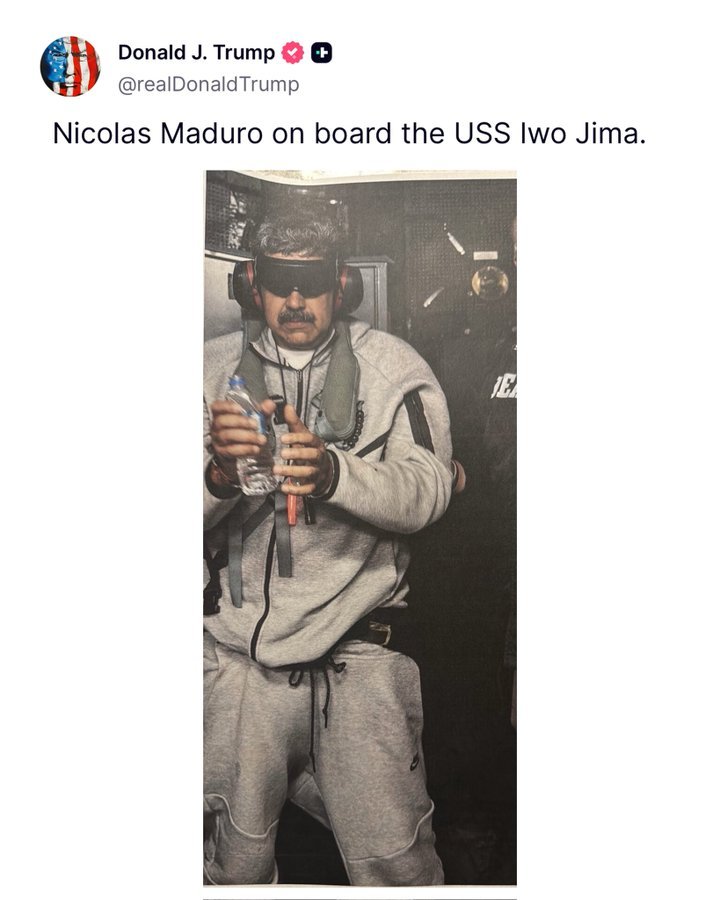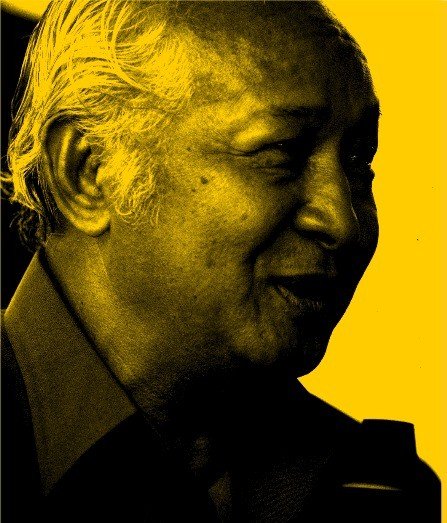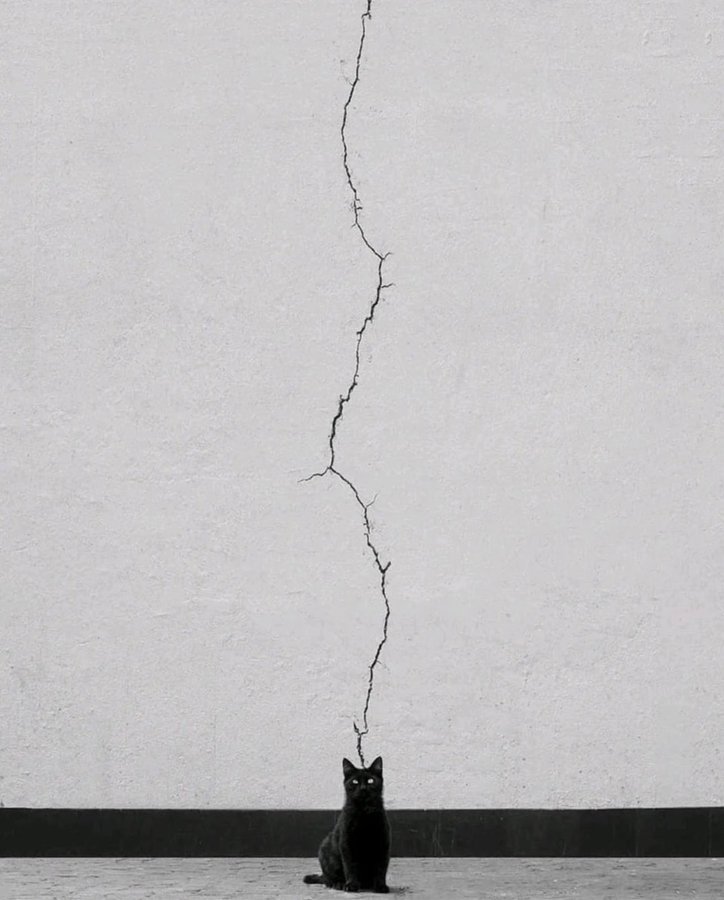Di zaman ketika keadilan tak lebih dari komoditas, bahkan kematian pun tidak membebaskan. Ia tidak membuat mereka yang tereksploitasi benar-benar lepas, karena dalam sistem kapitalisme, kematian hanyalah akhir dari produktivitas. Serial Korea Oh My Ghost Clients (2025), membawa kita pada kisah Noh Mu-jin, seorang advokat buruh yang, setelah pengalaman mati suri, mulai melihat hantu-hantu buruh yang masih bergentayangan karena keadilan atas kematian mereka tak terselesaikan. Akan tetapi, alih-alih menjadi kisah horor spiritual, serial ini justru menunjukan ironi dalam kapitalisme kontemporer.
Sebelum Anda membaca lebih jauh dan kecewa, saya perlu memberikan disclaimer bahwa tulisan ini tidak menyentuh aspek teknis perfilman seperti sinematografi, akting, atau penyutradaraan The Ghost Clients. Karena, jujur, saya sendiri memang tidak paham. Tulisan menggunakan salah satu kerangka yang dikembangkan Martin Suryajaya dalam Meta-Estetika; pendekatan yang digunakan berangkat dari spektrum reflektif: jauh, dalam, luas, dan mediatif. Film ini dibaca sebagai teks budaya yang mengandung struktur ideologis dan gejala simbolik, bukan sekadar karya estetika.
Dalam beberapa episode, kita akan menyaksikan bagaimana pekerja magang dipaksa lembur tanpa upah dan berakhir tewas karena kecelakaan kerja. Ini bukan insiden personal, tapi akibat langsung dari sistem kerja yang mengakomodir praktek labor market flexibility yang eksis hari ini. Sistem magang dipakai untuk menyamarkan relasi kerja sebenarnya, membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum, dan memperlakukan pekerja muda sebagai tenaga kerja yang bisa dibayar murah bahkan gratis.
Demikian pula kisah perawat yang bunuh diri karena perundungan di tempat kerja. Ini mencerminkan kekerasan simbolik dan psikologis dalam sistem hierarki kerja yang kompetitif dan tidak manusiawi. Di sektor seperti kesehatan dan pendidikan, relasi otoriter dan beban kerja berlebih membentuk kultur disipliner yang kejam, dan disangga oleh logika efisiensi institusional. Pekerja yang teratomisasi cenderung tak melihat diri sebagai kelas; akibatnya, kekerasan dari atasan kerap dilampiaskan secara horizontal kepada rekan yang dianggap lebih lemah—sebuah siklus penindasan yang berlangsung karena dominasi telah diinternalisasi, dan secara psikologis menyerupai displacement dalam psikoanalisis: dorongan yang tak bisa ditujukan ke atas, dialihkan ke sasaran yang lebih lemah di bawah.
Dalam kasus pekerja kebersihan di universitas, kita melihat bagaimana pengusaha/atasan tidak lagi memecat pekerja secara terang-terangan, melainkan melalui mekanisme “peningkatan kapasitas” yang bersifat manipulatif. Tes keterampilan dijadikan alat seleksi yang membungkus kebijakan efisiensi. Merekayasa situasi seolah-olah mereka yang diberhentikan tidak kompeten, membebaskan institusi dari tanggung jawab sosial sembari mempertahankan citra profesional.
Salah satu bentuk paling vulgar dari kekerasan struktural tampak di film itu adalah ketika tragedi kecelakaan kerja massal, di mana perusahaan luput dari jerat hukum. Dengan memecah struktur bisnis ke dalam unit-unit yang secara hukum tampak terpisah, perusahaan induk menempatkan kadernya di posisi strategis tanpa harus memikul tanggung jawab langsung. Asuransi digunakan sebagai instrumen kompromi, menjadikan uang santunan sebagai substitusi atas keadilan substantif. Di tengah tekanan ekonomi, keluarga korban kerap terpaksa menerima. Lebih ironis lagi, perusahaan tersebut tetap beroperasi dengan mengganti nama, seolah tragedi tak pernah terjadi—menggambarkan bagaimana sistem hukum dan ekonomi justru menyediakan mekanisme impunitas, alih-alih mendorong pertanggungjawaban dan pembaruan struktural.
Slavoj Žižek, filsuf dari Slovenia, yang menaruh perhatian besar pada momen-momen di mana “the Real” —dalam istilah Jacques Lacan, dimensi dari pengalaman yang tak dapat sepenuhnya dilambangkan atau ditenangkan oleh sistem simbolik—muncul untuk mengganggu realitas simbolik yang tampak utuh: dunia hukum, profesi pengacara, sistem keadilan buruh, media, opini publik, dan seterusnya. Hantu-hantu dalam Oh My Ghost Clients adalah manifestasi dari antagonisme yang ditekan oleh ideologi neoliberal: kematian akibat relasi kerja eksploitatif kapitalisme. Mereka menjadi simbol dari “return of the repressed”—yakni kemunculan kembali konflik kelas yang selama ini ditekan dan disingkirkan oleh wacana hukum dan kapital, tapi kini muncul dalam bentuk gangguan yang menginterupsi. Mereka kembali (sebagai hantu) karena sistem tidak memberi ruang bagi ketidakadilan yang mereka rasakan untuk diakui, apalagi diselesaikan. Jadi, kemunculan mereka adalah cara kebenaran yang tertekan memaksa muncul ke permukaan, meskipun lewat jalur supranatural.
Mu-jin, yang awalnya oportunis, menjadi advokat buruh bukan karena idealisme, melainkan karena tak punya pilihan lain, ia terdorong oleh kondisi struktural, bukan panggilan moral. Suatu hari, saat Mu-jin dan timnya melakukan inspeksi ke sebuah perusahaan dengan standar keselamatan kerja yang buruk, yang telah memakan korban jiwa, bahkan ia sendiri nyaris tewas tertimpa besi baja. Dalam momen hidup-mati itu, ia ‘bertemu’ dengan entitas supranatural yang memberinya tawaran: ia bisa tetap hidup jika bersedia membantu arwah para buruh yang mati akibat eksploitasi kerja. Mu-jin menyetujui kontrak itu karena terpaksa. Namun seiring waktu, keterlibatannya yang semula dipaksakan perlahan berubah menjadi panggilan etis. Ia mulai terlibat, bukan demi kontrak, tapi karena rasa tanggung jawab.
Demi memecahkan kasus dan menekan perusahaan, Mu-jin dan timnya menggunakan berbagai cara, salah satunya media sosial dan livestream sebagai alat kampanye. Mereka tahu sistem hanya merespons jika kasusnya menjadi viral. Inilah bentuk cynical ideology menurut Žižek: mereka sadar sedang memainkan sistem yang manipulatif, tapi tetap melakukannya karena berhasil, bahkan memuaskan. Keadaan yang menggambarkan bahkan keadilan sekalipun baru bisa bisa hidup kalau dikemas seturut logika kapitalisme—di mana nilai dari penderitaan ditentukan oleh viralitas dan bisa dijualnya peristiwa tersebut. Kita melihat bukan hanya bagaimana keadilan dimediasi oleh algoritma, tapi juga bagaimana publik sendiri mulai menikmati ketidakadilan sebagai tontonan moral. Di sinilah muncul jouissance—kenikmatan dari menyaksikan penderitaan, seolah-olah kita berpihak, padahal hanya menikmati dramatisasinya.
Yang menarik juga dari film ini adalah bagaimana ia memperlihatkan komodifikasi atas kematian. Para roh yang menuntut keadilan tidak direspons melalui ritual atau penghormatan, melainkan lewat advokasi hukum dan tekanan publik. Dalam sistem kapitalisme, kematian buruh bukanlah tragedi yang mengguncang, melainkan sesuatu yang sangat biasa seperti mesin rusak yang perlu diganti. Karena kapitalisme tidak mengenali tubuh manusia sebagai subjek etis, melainkan sebagai komponen dalam rantai produksi. Di titik ini, kematian bukan hanya dipinggirkan, tapi dijadikan bagian dari kalkulasi profit: siapa yang bisa diganti, seberapa cepat, dan dengan biaya berapa.
Agar memiliki nilai, kematian itu harus dikemas menjadi tontonan. Keadilan pun hadir bukan karena ada perubahan sistemik, melainkan karena celah dalam sistem dimanfaatkan untuk sementara. Padahal, keadilan sejati hanya mungkin jika sistem yang menghasilkan kematian dan ketimpangan itu diubah secara mendasar. Karena tanpa itu, setiap bentuk ‘kemenangan’ akan hanya menjadi episode dalam logika spektakel—ketidakadilan tidak dihapus, melainkan dipertontonkan dan dikonsumsi sebagai sesuatu yang menghibur, menyentuh, lalu dilupakan.
Namun di tengah paradoks inilah terdapat secercah harapan: dalam momen ketika the Real menembus fantasi ideologis, subjek punya peluang untuk berubah. Mu-jin, yang awalnya hanya ingin bertahan hidup, mulai melihat kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai panggilan etis. Transformasi ini membuatnya tak sekadar membela roh-roh penasaran, tetapi juga para buruh yang masih hidup, yang tertindas oleh sistem yang sama. Di kondisi ini juga muncul potensi politik, di mana kesadaran individu tumbuh dari trauma, dan bahkan membuat celah untuk perubahan yang jauh lebih radikal.
Dengan demikian, Oh My Ghost Clients bukan sekadar hiburan tentang seseorang yang kehilangan pekerjaan, lalu menjadi advokat buruh dan berurusan dengan roh penasaran. Serial ini adalah alegori kontemporer tentang cara kerja ideologi: bagaimana sistem menekan konflik kelas dan kekerasan struktural, lalu mengemasnya sebagai hiburan. Keadilan buruh memang ditampilkan, tetapi hanya setelah dikomodifikasi—dijual ulang sebagai konten viral yang bisa dinikmati publik. Di titik inilah kritik Žižek menjadi relevan. Seperti yang ia tegaskan, “the task today is not to penetrate to some hidden truth behind the fantasy, but to recognize the fantasy as such.” Maka tugas kita bukan bukan sekadar membongkar ilusi di balik tontonan, melainkan menyadari bagaimana kita sendiri menikmati ketidakadilan yang ditampilkan secara estetis—dalam bentuk tawa, air mata, dan rating yang tinggi.
Penulis: Benni
Editor: Redaksi