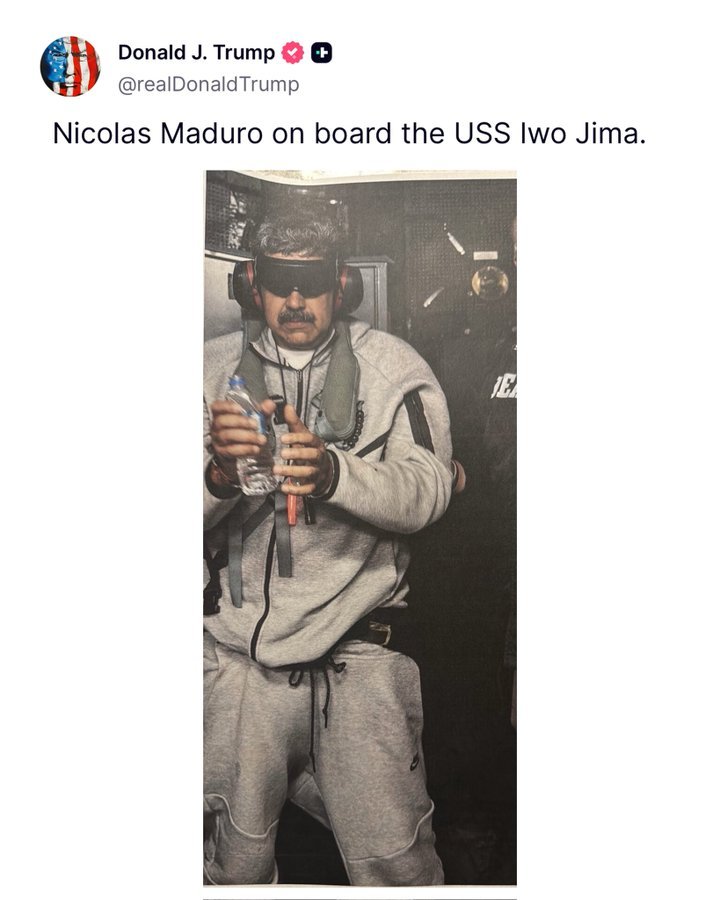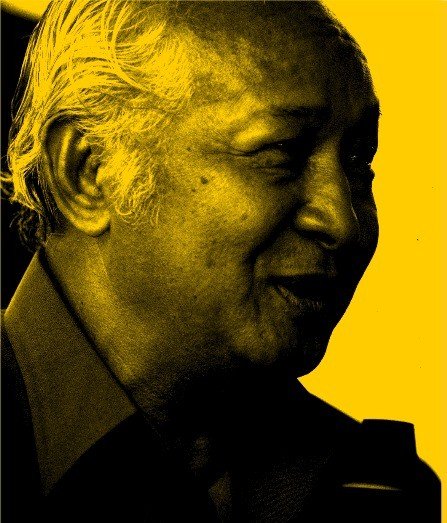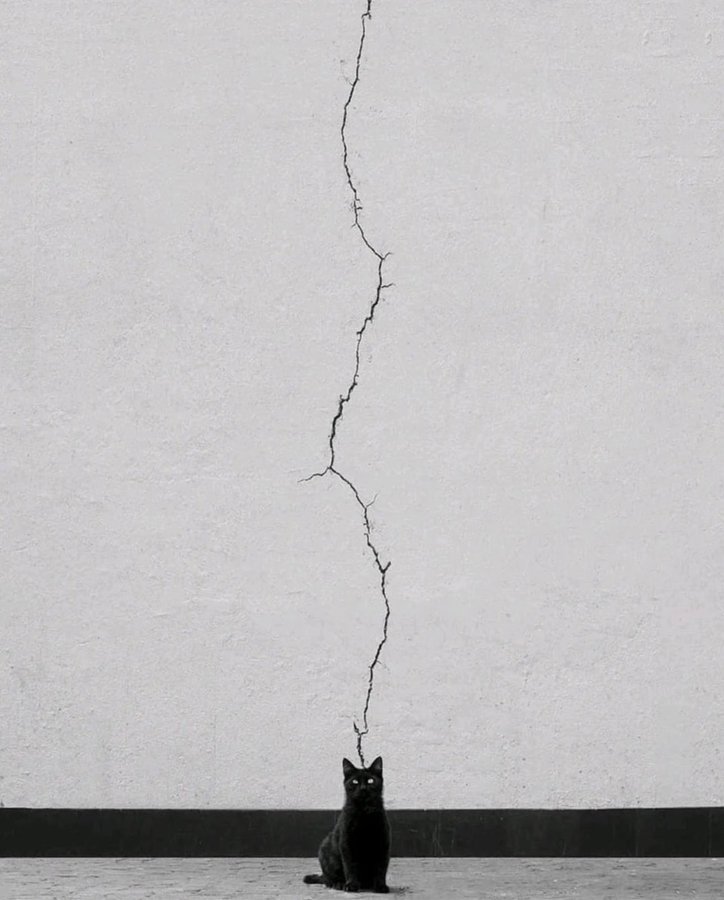Apa yang terjadi di Sumatera hari ini bukanlah bencana alam. Hujan turun sebagai bagian dari siklus iklim yang alamiah, bukan ancaman. Yang menjadikannya bencana adalah kerusakan lingkungan yang berlangsung lama, terstruktur, dan dibiarkan terjadi. Bahwa banjir, banjir bandang, dan longsor bukan muncul karena alam murka, tetapi karena penyangga alam yaitu hutan, sungai, dan kawasan resapan sudah dihancurkan.
Selama bertahun-tahun, negara terus memberikan izin ekspansi, ekstraktif, dan eksploitasi kapitalisme, hingga akhirnya merusak keseimbangan ekologis tersebut. Bukanlah tidak sulit kita mendapati informasi tentang bagaimana negara dengan mudahnya memberikan izin konsesi dan alih fungsi kawasan lindung oleh penguasa kepada para pengusaha.
Inilah gambaran jelas bagaimana sistem ekonomi kapitalisme bekerja. Sistem inilah yang menempatkan alam semata sebagai komoditas dan sumber akumulasi. Dalam logika kapitalisme, hutan bukanlah ruang hidup, melainkan sumber daya yang harus diekstraksi untuk menumpukkan kekayaannya.
Maka, kerusakan ekologis di Sumatera hari ini adalah dampak dari sistem, bukan peristiwa alam. Padahal, masyarakat Sumatera sudah sejak lama mengirim tanda bahaya. Dari hilangnya tutupan hutan di Aceh dan Sumatera Utara, sedimentasi parah di Sungai Kampar dan Batanghari, penurunan drastis kualitas tanah di Jambi, hingga longsor berulang di wilayah Sumatera Barat.
Daerah yang terdampak yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Detik News tanggal 28 November 2025 yang dipublikasikan pukul 18.02, tercatat total ada 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang. Di Aceh, 35 orang meninggal dunia dan 25 orang hilang. Kemudian, di Sumatera Barat tercatat ada 23 orang meninggal dunia, 12 orang hilang, dan 4 jiwa luka. Total ada 3.900 keluarga yang terdampak. Kemudian, di Sumut total ada 116 korban meninggal dunia dan 42 orang hilang.
Satya Bumi menyebutkan wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga sebagai wilayah paling parah. Data Walhi Sumut menunjukkan Ekosistem Batang Toru, sebagai hutan penyangga hidrologis, terus terkikis dan berkontribusi besar atas bencana ini.
Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru merupakan salah satu bentang hutan tropis esensial terakhir di Sumatera Utara. Luas administratif bentang alam ini sebesar 66,7 persen berada di Tapanuli Utara, seluas 22,6 persen di Tapanuli Selatan, dan seluas 10,7 persen di Tapanuli Tengah. Bentang alam ini pun merupakan bagian dari Bukit Barisan, dan menjadi sumber air utama, mencegah banjir dan erosi, serta menjadi pusat Daerah Aliran Sungai (DAS) menuju wilayah hilir.
Terdapat tujuh korporasi yang terindikasi menyebabkan kerusakan bentang alam Batang Toru:
- PT Agincourt Resources – Tambang Emas Martabe
- PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru
- PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu
- PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal di Tapanuli Utara
- PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan
- PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah
- PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan
Ketujuhnya beroperasi di atau sekitar Ekosistem Batang Toru, habitat orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, dan spesies dilindungi lainnya.
Yang harus kita ketahui adalah para korban ini justru berasal dari kelompok masyarakat yang tidak menikmati manfaat ekonomi dari eksploitasi alam, tetapi paling besar menanggung akibatnya. Ribuan keluarga kehilangan rumah, lahan, dan masa depan, dan ratusan orang kehilangan nyawa. Setiap kali bencana terjadi, negara kembali berlindung di balik narasi “bencana alam” untuk menghapus jejak tanggung jawab struktural.
Narasi yang menyesatkan publik, seolah air hujan adalah biang keladi dari semua kehancuran. Musuh kita bukanlah hujan, musuh kita adalah para korporasi perusak lingkungan. Selama bertahun-tahun, musuh ini mengikis hutan, merusak daerah resapan air, memotong lereng Bukit Barisan, menancapkan konsesi tambang, energi, dan perkebunan tanpa memikirkan keselamatan ekologis masyarakat di sekitarnya.
Dan lebih dari itu, musuh kita juga adalah para penguasa yang membuka pintu, memberi izin, dan melindungi operasi mereka atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kita sedang menghadapi bencana yang diproduksi, bukan bencana alam. Dan karena ia diproduksi, maka ia memiliki pelaku.
Karena itu, kita tidak boleh lagi membiarkan negara menyebut ini sebagai bencana alam. Narasi itu hanya digunakan untuk mencuci tangan, menghilangkan jejak tanggung jawab, dan membebaskan para perusak dari tuntutan hukum. Menyebut ini sebagai bencana alam berarti melepaskan pelaku dari jerat keadilan.
Perlakukan tindakan mereka sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan korban massal, yaitu para korporasi yang disebutkan. Wajiblah kita membuka ruang bagi penyelidikan, pengadilan, dan pemulihan ekologis yang sejati.
Karena skala kerusakan dan jumlah korban yang begitu besar, tragedi ekologis di Sumatera ini harus segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Penetapan sebagai Bencana Nasional adalah langkah politik dan hukum yang penting untuk membuka pintu penyelidikan menyeluruh terhadap siapa saja yang mengambil keuntungan dari penghancuran ekosistem yang menjadi penyangga hidup masyarakat.
Status Bencana Nasional memungkinkan dibentuknya tim investigasi lintas kementerian, akademisi, dan organisasi lingkungan. Tujuannya untuk menelusuri rantai kebijakan dan praktik korporasi yang terlibat. Inilah satu-satunya jalan agar para pelaku kerusakan lingkungan dapat diadili secara terbuka dan akuntabel. Mereka yang merusak harus diadili serta diberi hukuman setimpal.
Inilah saatnya untuk berhenti menganggap tragedi-tragedi ini sebagai peristiwa insidental. Kita harus menyebutnya sesuai realitasnya, bencana ekologis akibat kapitalisme ekstraktif, ekspansif, dan eksploitatif.
Penulis: Ahmad Sayyidulhaq Arrobbani Lubis anggota KPR Medan